Dalam
khazanah teologi Islam klasik, diskursus mengenai sifat-sifat Allah
Swt. cukup intens dibicarakan, baik sifat Allah yang berjumlah empat
puluh satu (wajib, mustahil, dan jawaz), maupun sifat para rasul yang
berjumlah sembilan. Diskursus mengenai sifat-sifat ini biasa
diistilahkan dengan akidah lima puluh.
Kecenderungan untuk mengetahui sifat-sifat Allah Swt. umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk menyucikan (taqdis)
Allah Swt. dari segala hal yang tidak layak dimiliki-Nya sebagaimana
tuduhan orang-orang musyrik, mengangkat tinggi-tinggi keagungan-Nya, dan
demi mengukuhkan keimanan umat manusia. Tujuan ini lebih didasarkan
pada realitas emosional dan psikologi manusia yang mudah terhipnotis
oleh keahlian dan kelebihan orang lain yang berada di luar daya
nalarnya.
Disamping
itu, analisa lain menyatakan bahwa penyematan sifat-sifat itu juga
didorong oleh faktor geofrafis dan struktur sosial masyarakat Arab yang
memang gemar memakai simbol-simbol tertentu sebagai media mengungkapkan
perasaan hati. Logika seperti ini juga dapat ditemui pada motif
pemberian mujizat kepada Nabi Saw. Allah Swt. memberikan al-Quran dan
mukjizat-mukjizat lainnya kepada Nabi Muhamad Saw. adalah agar misi
dakwahnya dapat diterima dan ajaran yang disampaikan dibenarkan.
Kepatuhan dan ketaatan tidak akan terwujud tanpa dibantu oleh
sebab-sebab berupa kelebihan dan keluarbiasaan yang dapat meluluhkan
hati masyarakat. Inilah salah satu bukti bahwa masyarakat Arab pada
umumnya menyukai simbol-simbol kelebihan dan keluarbiasaan, yang tetap
melekat hingga berabad-abad berikutnya. Simbolisasi itupun pada akhirnya
merambah pada tataran akidah ketuhanan; dimana bukti kemahakuasaan
Allah Swt. dan kebenaran Nabi SAW. perlu ”disimbolkan” melalui
penyematan sifat-sifat tertentu, melalui apa yang kita kenal dengan
sebutan sifat 50 itu. Disamping perlu dicatat, sifat-sifat tersebut
telah terurai dalam al-Quran.
Mengenal Zat (Entitas) Tunggal
Penelusuran
sifat-sifat ketuhanan dimulai dengan bukti eksistensi konsep Tuhan
sebagai Ada (dengan ”A” besar) yang Niscaya (juga dengan ”N" besar) atau
Niscaya Ada (Wajib al-Wujud). Ada yang Niscaya adalah sesuatu
yang tidak mungkin dipikirkan ketidakadaannya. Coba pikirkan bagaiman
sesuatu yang ada itu tidak ada, pastilah kita akan menemui kontradiksi.
Jadi, Niscaya Ada alias Wajib al-Wujud itu adalah keber-Ada-an
yang dipastikan wujudnya. Namun, ini hanya membuktikan sebuah
keber-Ada-an itu adalah ada yang semua orang tahu.
Kemutlakan
Tunggal adalah inti ajaran Islam. Tuhan adalah pencipta semua wujud
yang lahir dan batin. Tuhan adalah Wujud Mutlak, yang menjadi sumber
dari semua wujud-wujud yang lain. Dengan demikian, semua wujud yang lain
adalah nisbi belaka, sebagai bandingan dari Wujud Hakiki atau Zat yang
Mutlak. Karena itu, Eksistensi Tuhan bukan untuk dilihat tapi untuk
diketahui, sebab melihat Tuhan dengan mata kepala adalah mustahil.
Manusia hanya dapat mengetahui Tuhan dengan mata hati tanpa dapat
menggambarkan dengan suatu yang bertempat dan berbentuk. Ibnu Khaldun mengatakan: ”Janganlah
sekali-kali Anda mempercayai sugesti yang dimunculkan oleh benak
pikiran bahwa Anda mampu mengetahui segala yang ada dan sebab-sebabnya,
mengetahui secara detil semua wujud. Sugesti semacam itu hendaklah
direndahkan sebagai kebodohan. Ketahuilah, setiap orang yang memiliki
persepsi kesan superfisial mengatakan bahwa seluruh wujud terjangkau
oleh persepsinya, dan bahwa wujud itu tidak akan melampauinya.
Kenyataannya, persoalan itu berbeda sama sekali, dan kebenaran berada di
belakangnya. Tidakkah Anda lihat orang yang tuli, bagaimana wujud
terbatas baginya pada persepsi keempat inderanya dan akalnya. Segala
yang dapat didengar bukan merupakan bagian dari wujud baginya. Demikian
pula orang yang buta, semua yang dapat dilihat bukan merupakan bagian
wujud baginya. Untuk orang cacat semacam itu, apabila kepada mereka
tidak diletakkan kesetiaan pada informasi yang diterima dari
bapak-bapak, guru-guru, dan orang lain, mereka tidak akan mengakui
eksistensi segalanya itu.
Pengakuan
terhadap keesaan Tuhan identik dengan pengerahan persoalan ini kepada
Tuhan yang menciptakannya dan yang menguasainya. Tidak ada pencipta
selain-Nya. Semua sebab-sebab itu meningkat kepada-Nya dan kembali
kepada kekuasaan-Nya. Kita mengetahui-Nya hanya lantaran kita muncul
daripada-Nya. Inilah penafsiran pernyataan yang dimunculkan oleh para shadiqin: ”Ketidakmampuan menemukan persepsi, itulah persepsi” (’Ajz al-idrak idrak).
Dalam keadaan tidak mungkin melihat Tuhan, yang harus diketahui manusia ialah usaha terus-menerus dan penuh kesungguhan (mujahadah)
kepada-Nya. Ini diwujudkan untuk merentangkan garis lurus antara diri
manusia dengan Tuhan. Garis lurus itu merentang sejajar secara
berhimpitan dengan hati nurani.
Karena
kemahaesaan-Nya dan kemutlakan-Nya, wujud Tuhan adalah wujud kepastian.
Justru Tuhanlah wujud yang pasti. Abu Hanifah berkomentar, tidak pantas
manusia berbicara tentang Zat Allah Swt. Sebab ia telah tercukupkan
dengan mengenal dan memahami sifat-sifat-Nya yang telah difirmankan.
Persepsi kemanusiaan tidak dibolehkan berbicara sifat-sifat ketuhanan
berlandaskan pada akal semata.
Tepat di titik ini, kelemahan manusia dalam memahami Wujud Eksistensial
Allah Swt. teruraikan. Manusia hanya mampu memahami sifat-sifat-Nya,
bukan Wujud eksistensial-Nya.
Memahami Sifat-sifat Allah
Sifat adalah kata bahasa Arab yang merupakan derivasi dari kata wasf (shifat)
yang telah diindonesiakan. Sifat dapat diartikan sebagai sebuah sebutan
yang dapat menunjukkan keadaan suatu benda. Atau lebih mudahnya, sifat
adalah ciri-ciri sesuatu. Dapat juga dipahami, sifat adalah sebuah
ciri-ciri (amârah) yang melekat pada diri seseorang dan dapat digunakan sebagai sarana identifikasi.
Dalam
ilmu teologi, term sifat menjadi faktor fundamen yang mempengaruhi
perbedaan dalam menentukan sifat-sifat Allah. Para mutakallim (teolog)
mengartikan sifat adalah suatu unsur selain zat dan tidak harus nampak
di luar zat. Pengertian semacam ini mendorong seseorang berpandangan
bahwa sifat wajib Allah Swt. berjumlah dua puluh, sementara teolog yang
mendefinisikan sifat sebagai unsur di luar zat dan harus nyata adanya,
mendorongnya berpendapat bahwa hitungan sifat wajib-Nya hanya berjumlah
tujuh.
Bagi
manusia yang berpikir dan berjiwa sehat akan mengakui eksistensi Wujud
Tuhan, bahkan meniscayakan Wujud-Nya. Karena fitrah yang terkandung
dalam hati nurani dan rasio di kepala, memaksakan mengenal Hakikat
Tunggal. Disamping, kalau mau sadar dan merenungi format kemanusiaan,
dari aspek lahir (jism) dan aspek batin yang meliputi nyawa,
nalar, atau unsur hewani, nabati, debu, pasir, batu, udara, angkasa, air
hujan, durasi waktu; ada siang ada malam, semua itu menjadi
indikasi-indikasi akan Wujudnya Tuhan.
Makanya, Allah Swt. berfirman surat al-Anfal [8]: 22-23:
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
“Sesungguhnya
seburuk-buruknya mahkluk berkaki (dabbah) di sisi Allah adalah orang
yang tuli dan bisu, yaitu orang-orang yang tidak mau berpikir.
Seandainya Allah akan memberi kebaikan terhadap mereka, maka Ia membuka
pendengaran mereka. Dan ketika Ia telah membuka pendengaran mereka, maka
mereka menolak dan berpaling”.
Meski
keajaiban-keajaiban tampak di depan mata, tapi Wujud Allah Swt. tidak
dapat diketahu oleh manusia. Eksistensi Tuhan adalah samar (ghaib)
menurut mata manusia dan jangkauan nalar. Kendati demikian, dengan
mengetahui tanda-tanda kebesaran-Nya maka nalar akan dapat menjangkau
Wujud Tuhan. Seandainya Ia berkehendak lain, dalam arti tidak
memperkenalkan kepada manusia melalui daya nalarnya, maka siapapun tidak
akan menemukan Eksistensi-Nya.
Tapi
bukti kosmologis memberi sumbangan pengetahuan kepada kita, bahwa Ada
yang Niscaya itu memang benar dan nyata. Keniscayaan Wujud Tuhan
terejawantah di balik keunikan-keunikan dan keanekaragaman bentuk
ciptaan-Nya. Nalar tidak dapat menerima kondisi tidak adanya Pencipta
ciptaan-ciptaan itu. Keberadaan ciptaan menunjukkan Wujudnya Sang
Pencipta, atau menurut konsep Aristotelian, Ia dibahasakan sebagai Prima
Causa (Penyebab Utama) atas keberadaan setiap yang ada. Menurut analisa Imam Ghazali, kalimat tauhid (baca: syahadat)
mengandung makna implisit akan keniscayaan Wujud Allah Swt.,
sifat-sifat-Nya, sifat tindakan-Nya, dan percaya atas kenabian Muhammad
Saw.
Dari situ pula bangunan iman berdasarkan pada empat komponen: (1)
Mengetahui Allah dan titik sentralnya pada sepuluh hal pokok: mengenal
Wujud Allah Swt., Qidam dan Baqa’-Nya, bukan bentuk nature (jauhar), bukan benda materi (jism), dan bukan berbentuk sifat (’irdh),
dan tidak membutuhkan ruang dan waktu, Dia akan dapat diketahui melalui
sifat-sifat-Nya dan Zat-Nya yang bersifat Esa; (2). Mengenal
sifat-sifat-Nya, dan berkisar pada sepuluh dasar; yakni memahami bahwa
keadaan Allah Swt. itu Hidup, Mengetahui, Berkuasa, Berkehendak,
Mendengar, Melihat, Benar berita-berita-Nya, Bersih dari menitis pada
ciptaan, dan semua sifat-sifat-Nya Qadim ; (3). Mengetahui
tindakan-Nya. Ini juga berkisar pada sepuluh hal pokok: Seluruh gerakan
makhluk adalah atas kontrol (ciptaan) dan kehendak-Nya, Ia memberi hak
bergerak (kasb ) pada makhluk dengan tidak lepas dari ciptaan dan
kehendak-Nya, keutaman Allah Swt. tidak bertambah dan berkurang sebab
makhluk karena kemulyaan-Nya mutlka, Allah Swt. boleh (dapat) juga
mentaklif manusia diluar kemampuannya karena kemutlakan kekuasaan-Nya
meskipun tidak akan terjadi,
Allah Swt. tidak berkeharusan menjaga yang terbaik, terutusnya Nabi
Muhamad merupakan kewenangan mutlak Allah Swt., dan kenabian Muhammad
Saw. tetap berlandaskan pada mu’jizat: (4). Percaya pada berita intuitif
(wahyu), yang berkisar pada sepuluh dasar: dikumpulkan (hasyr) di hari kiamat, nasyr, siksaan kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, timbangan amal, melewati shirath (tangga akhirat), terciptanya surga dan neraka, dan hukum pemerintahan. Semua sifat-sifat Tuhan dan tata nilai di muka telah diuraikan secara baik dalam al-Quran atau hadits.
Sedangkan
dalam pandangan Muhamad Amin, implikasi ayat al-Quran yang mengurai
sifat-sifat Allah Swt. menunjukkan tiga prinsip dasar, yang seandainya
terpenuhi maka akan memperoleh substansinya dan terjamin kebenarannya.
Tapi salah satu diantara ketiganya tidak boleh ada yang dialpakan.
Ketiga prinsip dasar itu adalah:
Pertama, prinsip mensucikan (tanzih) Zat Allah Swt. dari segala bentuk keserupaan dengan ciptaan, baik dalam Zat-Nya, pekerjaan-Nya dan sifat-sifat-Nya. Hal Ini dibangun atas dasar surat al-Syura [42]: 11:
ليس كمثله شيء
“Tidak ada sesuatu-pun yang menyerupai Dia”
Dan surat al-Nahl [16]: 74. yang berbunyi:
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وانتم لا تعلمون
“Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui”.
Kedua,
prinsip percaya dan menerima sifat-sifat Allah Swt. dari kutipan wahyu
(baca: firman-Nya). Logikanya, kelemahan dalam mengetahui Zat Allah Swt.
sudah pasti akan menyebabkan kemustahilan mengetahui sifat-sifat-Nya.
Dengan demikian, menerima dan membenarkan berita yang berasal dari wahyu
adalah sebuah keniscayaan. Siapakah yang dapat mengetahui Zat Allah
Swt. kalau bukan diri-Nya?.
Ketiga,
percaya dan menerima sifat-sifat Allah Swt. dari hadits Nabi. Sebab
setiap perkataan Nabi Saw. adalah semata-mata atas komando Allah Swt.
Karena itu, esensi hadits-hadit Nabi tidak lain adalah esensi dari wahyu
Allah Swt., -sama sekali tidak menyimpang dengan wahyu. Hal itu telah
dijelaskan dalam al-Quran surat al-Najm [53]: 3-4:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
“Dia (Muhamad) tidak berkata berdasar hawa nafsunya, tiadalah ia kecuali wahyu yang diwahyukan.”
Itulah
prinsip-prinsip dasar untuk mengetahui sifat-sifat Allah Swt. dan
mengetahui Substansi Ketuhanan nan Sejati. Semua orang tahu, bahwa
menyifati benda materi bukanlah hal yang sulit. Tapi menyifati entitas
yang di luar jangkauan nalar, Wujud Tunggal, Eksistensi Abstrak,
mustahil ada yang mampu mengetahui-Nya. Langkah yang harus ditempuh
adalah pendekatan melalui pesan-pesan ketuhanan. Dengan cara inilah
hakikat ketuhanan akan diketahui melalui sifat-sifat-Nya.
Mengenai
universalitas sifat-sifat Allah Swt., secara garis besar bahwa Ia tidak
mempunyai kemiripan dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga ketika
ditemukan teks-teks wahyu yang bila dipahami secara eksplisit akan
menimbulkan kesan keserupaan sifat-sifat Allah Swt. dengan sifat
makhluk-Nya, misalkan sama’ [mendengar] dan bashar [melihat],
menurut Muhamad Amin, tidak berarti sifat tersebut harus dihapus (tidak
diterima) atau disamakan dengan makhluk. Penyematan sifat-sifat itu
merupakan isyarat bahwa Ia memiliki sifat sama’ dan bashar, misalnya, akan tetapi wujud dan bentuknya berlainan dengan sifat yang dimiliki makhluk. Karena walau bagaimana pun, tidak ada sesuatu-pun yang menyerupai-Nya.
Jadi
harus dipahami bahwa kebenaran riil mengenal sifat-sifat Allah swt.
harus selaras dengan ketentuan tiga prinsip dasar di muka. Kemudian
dalam perkembangannya, penuturan sifat-sifat Allah Swt. sebagian ada
yang dilandasi wahyu dan sebagian lagi berlandaskan nalar-rasionil.
Spesifikasi 50 Sifat
Para mutakallim membagi lima puluh sifat Allah Swt. menjadi sifat wajib, muhal, dan jawaz. Menurut Imam al-Haramain,
pemahaman tiga bentuk sifat ini tergolong sebagai konsumsi akal
(rasional). Sehingga bagi orang yang tidak mampu memahami kehendak
sifat-sifat tersebut berarti tidak berakal. Digambarkan bahwa kalau
dikatakan Allah Swt. itu wajib bersifat, seumpama qudrah (kuasa), tentunya akal memahami bahwa ketiadaan sifat kuasa bagi-Nya tidak mungkin akan diterima akal.
Tapi
sebelum mengenal partikulasi sifat-sifat Allah Swt., secara global
harus diyakini bahwa Zat Tunggal Allah Swt. selalu bersanding erat
dengan segala sifat purna, hampa dari bermacam-macam kekurangan (cacat),
dan berwenang melakukan dan meninggalkan segala hal yang potensial
wujud (baca: mumkinat). Perincian ke 50 sifat itu adalah sebagai berikut:
I. Sifat-sifat Allah Swt.
1) Sifat Wajib Allah Swt. berjumlah dua puluh. Kemudian jumlah dua puluh sifat ini dikelompokkan menjadi empat, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma’ani, dan ma’nawiyah. (1). Nafsiah, adalah sifat yang berhubungan dengan keberadaan Zat Allah Swt. Ini hanya memiliki satu sifat, yaitu sifat wujud (Eksistensi Tuhan). (2) Salbiyah,
dapat diartikan sebagai jenis sifat yang dipahami untuk
meniadakan-menyangkal- ketidaklayakkan dan ketidaksesuaian bagi Allah
Swt. Dinamakan salbiyah (terlepas) karena motifasi penyifatan ini
bertujuan menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Swt. Adapun
sifat-sifat yang terekrut dalam Salbiyah meliputi sifat qidam; dahulu tanpa permulaan, baqa; kekal, mukhalafah li al-hawadits; berbeda dengan makhluk, qiyamuhu bi nafsih: eksis dengan Zat sendiri, dan wahdaniyah: Maha Esa. Sifat salbiyah dapat digambarkan seperti sifat qidam (dahulu tidak berawal), misalnya, berarti bahwa wujud Allah Swt sudah ada sejak semula tanpa di dahului sesuatupun. Jadi sifat qidam ini menolak sifat kebaharuan; (3) Ma’ani,
adalah sifat wajib bagi Allah Swt yang dapat digambarkan oleh akal
pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang karena kebenarannya dapat
dibuktikan oleh pancaindera. Yang termasuk ke dalam sifat ma’ani ada tujuh sifat, antara lain sifat qudrat; kuasa, iradat: kehendak, ilm: pengetahuan, hayat: hidup, sama’: mendengar, bashar: melihat, dan kalam: bicara. (4) Ma’nawiyah, sifat yang berhubungan dengan sifat ma’ani, atau merupakan kelanjutan logis dari sifat ma’ani. Sifat yang masuk dalam bagian ini ada tujuh, kaunuhu qadiran: Keberadaan-Nya Maha Kuasa, kaunuhu muridan: Keberadaan-Nya Maha Berkehendak, kaunuhu ’aliman: Keberadaan-Nya Maha Mengetahui, kaunuh hayyan: Keberadaan-Nya Maha Hidup, kaunuh sami’an: Keberadaan-Nya Maha Mendengar, kaunuhu bashiran: Keberadaan-Nya Maha Melihat, dan kaunuhu mutakalliman: Keberadaan-Nya Maha Berbicara. 2) Sifat Muhal (kebalikan
sifat wajib) juga ada dua puluh. Lebih mudahnya bahwa sifat wajib
adalah sesuatu yang sudah pasti dimiliki Tuhan, sebaliknya, sifat muhal sudah
pasti tidak ada pada Zat Allah Swt. Jadi disamping orang muslim wajib
memahami sifat Allah Swt juga harus paham dengan sifat yang tidak layak
dimiliki-Nya. Yakni kaharusan meniadakan sifat-sifat muhal yang berjumlah dua puluh pada Zat-Nya. 3) Sifat Jawaz
hanya satu. Sifat ini diibaratkan hak wewenang Tuhan dalam bertindak.
Segala realitas yang dihubungkan dengan eksistensi Allah Swt. untuk
berbuat (jaiz) sebenarnya bukan bagian sifat yang menetap pada
Zat-Nya, melainkan sebuah sifat yang berhubungan dengan Kuasa-Nya. Jadi
jangan disalahpahami bahwa Zat Allah Swt. tersifati dengan jawaz. Yang benar bahwa Zat Allah Swt. hanya tersifati dengan sifat-sifat wajib. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sifat jawaz
Allah Swt. ialah hak wewenang Tuhan. Adalah rasional bila Allah Swt.
mungkin melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya, tanpa terikat
dengan segala apapun.
II. Sifat-Sifat Rasul
1) Sifat Wajib yang ada pada rasul jumlahnya ada empat: (shidq) jujur dalam bicara, (amanah) terpercaya menjauhi perbuatan haram dan makruh, (fathanah) kecerdasan dan kemampuan mengalahkan lawan atau menyirnakan ajaran sesatnya, dan (tabligh)
menyampaikan pesan Allah Swt. kepada umat manusia sesuai perintah-Nya.
Dengan terbuka, sifat wajib ini harus dipahami bahwa akal tidak menerima
keberadaan seorang rasul yang tidak bersifat seperti ini.
2) Sifat Muhal, juga ada lima: (kidzib) berdusta, (khianat) tidak konsekwen terhadap perbuatan halal dan haram, (baladah) bodoh atau lemah pemahaman (Jawa: blôon), dan (kitman)
menyembunyikan pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada umat manusia.
Dengan sifat-sifat ini, secara rasional, diartikan bahwa para rasul
tidak akan memiliki sifat-sifat yang demikian. Akal tidak akan menolak
wujudnya sifat-sifat ini pada diri rasul.
3) Sifat Jawaz
bagi Rasul ialah kebolehan melakukan perbuatan manusiawi yang tidak
mengurangi kemulyaan derajatnya. Dengan sifat ini, para Rasul juga
memiliki sifat-sifat dasar manusiawi, seperti berjalan, makan, minum,
dan lain sebagainya. Tapi semua itu tidak mengurangi sifat mulia mereka.
Kontroversi Sifat-sifat Allah
Dalam
ranah teologi, pembagian sifat-sifat wajib Allah Swt. menjadi 20 sifat
tidak disepakati semua mutakalimin. Mereka masih mempermasalahkan,
terutama tentang konsep alam realitas. Menurut al-Sanusi, sebuah
realitas terbagi dalam empat bagian: nyata adanya, nyata ketiadaannya,
perihal keadaannya, dan perihal anggapannya. Contoh yang nyata adanya
adalah tubuh manusia, dan contoh yang nyata tidak adanya adalah manusia
sebelum kelahirannya. Sedangakan hal keadaan adalah seperti keberadaan
Umar yang berkuasa (menjadi presiden, misalnya), dan perihal
pengungkapan seperti penetapan bahwa umar bersifat kuasa. Pada akhirnya,
al-Sanusi menetapkan bahwa sifat wajib Allah Swt. berjumlah dua puluh.
Sementara
menurut Abu Hasan Asy’ari, sifat yang berhubungan dengan sifat keadaan
ditiadakan karena dianggap sesuatu yang irasional. Mayoritas teolog yang
selaras dengan pemikiran Asy’ári, akhirnya tidak mengaitkan sifat yang
berhubungan dengan keadaan, dan menyatakan sifat wajib Allah Swt. hanya
dua belas. Sifat Ma’nawiyat (baca: kaunuhu bashiran
dan lain-lain) digugurkan. Mereka tidak setuju bila Allah Swt. disifati
dengan sifat keberadaan-Nya berkuasa. Bahkan menurut al-Asy’ari, yang
gugur bukan hanya sifat ma’nawiyah, tapi juga sifat wujud (nafsiyah). Karena sifat wujud tidak lain hanyalah Entitas Zat (’ain al-dzat)
itu sendiri, bukan sesuatu yang lain. Sebab jika dikatakan Wujud Allah
Swt. berarti yang dimaksud adalah bentuk Zat-Nya, bukan sifat-Nya. Perbedaan
ini dikomentari oleh Muhamad Fadhali. Menurutnya, bagi tingkat awam
cukup dikatakan bahwa sifat keberadaan itu merupakan akar dari
sifat-sifat ma’ani.
Meskipun secara eksplisit, komentar itu tidak memberi corak pemikiran
lain atau pemihakan, tapi komentar tersebut sangat signifikan, mengingat
kebutuhan teori akidah (sifat) kaum awam adalah akidah instan, yakni
teori akidah yang gampang diterima secara langsung dan tidak membutuhkan
pemikiran terlalu dalam. Berbeda dengan Muhamad Amin. Ia berasumsi bahwa sifat ma’nawiyah tidak lebih dari sekedar cara jitu untuk menyifati Allah Swt. -memudahkan pemahaman- dengan sifat-sifat ma’ani. Sehingga wajar bila para teolog (mutakallim) yang berasumsi demikian menyatakan bahwa sifat ma’nawiyat merupakan mediasi (washithah tsubutiyyah [sarana pendukung pasti]), bukan justru menafikan maupun menetapkan sifat-sifat Allah Swt yang hakiki.
Pandangan semacam itu, menurut Muhammad Amin, hanya dibuat-buat dan
merekayasa akidah dari sebagian kalangan mutakallimin saja. Sebab,
demikian kilah Amin, akal sehat tentunya tidak perlu perantara dalam
menetapkan sesuatu dan menafikannya. Dapat dipastikan bahwa setiap suatu
yang tidak ada sudah tentu tetap berada dalam ketiadaan, dan suatu yang
ada sudah pasti tergolong sebagai realitas yang wujud. Dan perlu
dicatat, tambah Amin, tidak ada istilah perantara dalam menetapkan dan
menafikan sesuatu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan para mutakallim di muka dapat dikerucutkan dalam dua kelompok berikut: (1). Ulama yang menilai bahwa sifat ma’nawiyat termasuk sifat hakiki. Menurut pendapat ini, sifat juga ada yang diperuntukkan (berhubungan) bagi perihal keberadaan (ahwal), yaitu sebuah sifat yang menetapkan wujud-Nya (keberadaan Allah Swt. bersifat qudrah, misalnya), bukan untuk menafikan atau mewujudkan sifat pada Zat-Nya. Dari latarbelakang pemikiran seperti ini, sifat ma’nawiyat dinilai termasuk sifat yang ada dan atau dimiliki oleh Zat Allah; (2).
Ulama yang berpandangan bahwa hal keberadaan bukanlah sifat, dan tidak
setuju bila ada semacam perantara dalam menetapkan ketiadaan atau wujud
suatu sifat. Pendapat ini menganggap cukup pada sifat ma’ani sebagai dasar pijakan mengetahui sifat-sifat Allah Swt. Adapun ma’nawiyat sebenarnya hanya sekedar piranti penunjang untuk menetapkan sifat ma’ani pada
Zat. Jika sekedar piranti penunjang, menurut ulama ini, tidak bisa
dikatakan sebuah sifat, karena sebuah sifat adalah sifat itu sendiri.
Lagi pula, realitas-faktualnya menunjukkan bahwa ma’nawiyat tidak terdapat dalam gambaran akal pikiran manusia.
Jika
diteliti lebih dalam, argumen kedua pendapat di atas lebih didasari
oleh pebedaan dalam mendefinisikan makna sifat itu sendiri. Bagi ulama
yang mengartikan sifat adalah sesuatu selain Zat, maka akan
mengartikannya sebagai seluruh jenis sifat, baik salbiyat, nafsiyat, ma’ani, atau ma’nawiyat.
Sedangkan ulama yang mengartikan sifat sebagai unsur yang nyata ada dan
menjadi tambahan (fakta eksternal) di luar Zat, tentu akan mengatakan
bahwa sifat hanya ”terdapat” dalam sifat ma’ani.
Benarkah Sifat Allah Terbatas dalam Akidah Lima Puluh
Lepas
dari kontroversi hitungan sifat-sifat Allah Swt. di atas, yang pasti
kalau sifat Allah Swt. bisa diketahui manusia dalam jumlah terbatas, ini
akan menimbulkan pertanyaan: Apakah hanya sebatas itu sifat-sifat Allah? Kalau terbatas itu, apa bedanya dengan sifat-sifat makhluk yang serba terbatas?
Sebelum
pertanyaan ini dijawab, perlu diketahui bahwa akidah Ahlussunah
wal-Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Swt. berdasarkan al-Quran
maupun hadits Nabi Saw. sama sekali tidak mengalami perubahan,
pergeseran, penambahan, pengurangan, penafian, atau bahkan penginkaran,
baik karena faktor keterasingan dalam pikiran atau karena dinilai berada
di luar batas nalar. Posisi akal dalam pandangan Ahlussunah wal-Jamaah
hanya menjadi alat bantu dalam memahami sifat-sifat Allah Swt., baik
merujuk fiman-Nya, catatan hadits, dan menjadi referensi hukum-hukum
Allah Swt. Sama sekali akal tidak memiliki otoritas dalam membentuk
syariat, menolak, atau bahkan menghapus ketentuan hukum yang berdasarkan
syariat.
Sifat-sifat
wajib Allah Swt., jika dirujuk dalam hadits-hadits Nabi Saw.,
sebenarnya tidak terbatas pada hitungan 20. Bahkan Nabi Saw. penah
menyatakan bahwa Allah Swt. memiliki sifat paripurna yang tidak
terhingga (tidak terhitung jumlahnya). Jadi, apabila Allah Swt. itu
bersifat sempurna dan paripurna, tentunya sifat-sifat pada Zat-Nya pun
tidak terhingga pula; tidak sebatas pada dua puluh sifat. Justru akan
sangat naif bila Tuhan bersifat terbatas dalam gambaran manusia.
Karenanya, sifat-sifat Allah Swt. hakikatnya tidak dapat tertuang hanya
dalam dua puluh sifat. Kalaupun para teolog menjelaskan bahwa sifat
wajib Allah Swt. hanya berjumlah dua puluh -lepas dari kontroversi
ulama- bukan berarti membatasi sifat sifat wajib-Nya. Akan tetapi lebih
didasari asumsi bahwa, dalam ranah teologi, ketika nalar tidak dapat
menjangkau, sementara wahyu tidak menerangkan, maka tidak ada tuntutan
bagi manusia untuk memahami atau membahasnya. Ini merupakan keputusan
Allah Swt. yang selalu disesuaikan dengan kadar kemampuan nalar manusia.
Bahkan bila direnungi, kemampuan manusia mengetahu ke 20 sifat-Nya
sudah merupakan fadhlullah (anugerah dari Allah) yang luar biasa.
Dari
sini dapat disimpulkan bahwa, manusia hanya diwajibkan mengetahui apa
yang dapat dijangkau oleh pikirannya. Sudah jelas bahwa semua sifat
Allah Swt. tidak dapat dicapai oleh manusia, mengingat kodrat manusia
yang terbatas dan berhingga. Karena itu, melalui panduan wahyu, manusia
diberi pengetahuan mengenai sifat-sifat-Nya sebatas pada sifat-sifat
yang memang mampu dinalar oleh keterbatasan akal manusiawi. Kebetulan,
sifat-sifat wajib yang dalam wahyu Allah Swt. dan hadits Nabi Saw. hanya
diberitahukan sebanyak 20 sifat. Dengan demikian, ke 20 sifat yang
mampu diketahui manusia inilah yang wajib ia ketahui dan ia yakini
kebenaran dan keberadaannya. Namun manusia jangan beranggapan bahwa
hanya sebatas itulah sifat-sifat yang dimiliki Allah Swt. Sifat Allah
Swt. Maha Tak Terhingga, Maha Sempurna, dan Maha Paripurna untuk dapat
dijangkau oleh pikiran manusia.
Koherensi Sifat dan Asmaul Husna
Asmaul
Husna adalah nama-nama baik (indah) yang dimiliki Allah Swt. Jumlah
nama-nama tersebut ada sembilan puluh sembilan. Namun sebelumnya, perlu
diingat kembali bahwa orientasi nama bukanlah penamaan tersebut dan
bukan pemilik nama. Dalam Asmaul Husna, yang dimaksud ialah sesuatu yang
melekat pada Zat Allah Swt., bukan Zat itu sendiri maupun unsur lain di
luar Zat-Nya. Sementara arti definitif sebuah nama ialah bentuk kalimat yang berfungsi untuk menunjukkan obyek yang mempunyai nama. Dalam sebuah hadits , Nabi Muhamad Swt. berpesan: ”Berperilakulah seperti perilaku (akhlaq) Allah”.
Akhlak Allah Swt. tersebut dapat ditemukan pada Asmaul Husna dan
sifat-sifat Allah Swt. Maksud hadits tersebut bukan bermakna kita
dianjurkan meniru hakikat perilaku-perilaku Allah Swt. secara sepadan
tanpa cela, melainkan diselaraskan dengan kadar kemampuan yang dapat
dilakukan manusia. Umpama Allah Swt. memiliki Nama Maha Dermawan (al-jawwâd),
maka kita dianjurkan meniru aplikasi dari sifat itu, yakni berperilaku
murah hati terhadap orang lain, bukan berbuat murah seperti yang
dilakukan Allah Swt. Jika ditilik dari aspek implikasinya, menurut al-Ghazali, konsepsi Asmaul Husna dipilah dalam sepuluh kelompok:
1. Nama yang menunjukkan Zat-Nya saja. Misalkan kalimat ’Allah’. Penamaan tersebut tentu mengenalkan pada Zat yang Niscaya Ada.
2. Nama yang disamping menunjukkan pada Zat-Nya, juga mengandung nilai salbu: pemblejetan hal-hal yang tidak layak ada pada Zat-Nya. Seperti al-Quddûs (Maha Suci), al-Ghaniy (Maha Kaya), dan lain-lain. Al-Quddûs:
Maha Suci berarti Zat-Nya Suci tanpa dapat digambarkan oleh semua
dugaan (prasangka) manusia, dan berarti pula memustahilkan hal-hal yang
menodai Kesucian-Nya.
3. Nama yang kembali pada Zat-Nya secara berhubungan. Seperti al-’Aliy, al-’Azhim, al-Awwal, al-Akhir, dan lain-lain. Al-’Aliy
dapat diartikan Maha Tinggi (Jawa: luhur), di atas ketinggian derajat
semua makhluk. Berhubungan yang dimaksud di sini adalah terdapat unsur
perbandingan dengan yang lain.
4. Nama yang kembali pada Zat-Nya dengan menafikan dan berhubungan. Semisal al-Mâlik dan al-’Azîz.
Gambarannya, Allah Maha Penguasa yang tidak butuh pada siapa pun
(menafikan), akan tetapi dibutuhkan oleh siapa pun (berhubungan).
5. Nama yang kembali pada Zat beserta sifat-sifat yang menetap. Misalkan al-Hayy, al-’Alîm, al-Qâdir, al-Murîd, al-Samî’, al-Bashîr, dan Mutakallim. Kalau kita katakan bahwa Allah Swt. Maha Mengetahui, ini berarti menunjukkan pada Zat-Nya yang bersifatan Mengetahui.
6. Nama yang kembali pada sifat Ilmu: mengetahui serta berhubungan. Seperti al-Hakîm, al-Khabîr, al-Syahîd, al-Muhshiy. Nama al-Hakîm (Pemberi
Keputusan), menunjukkan pada sifat Ilmu-Nya yang berhubungan dengan
kemulyaan pengetahuan yang melebihi pengetahuan makhluk.
7. Nama yang kembali pada sifat Qudrat serta bertambah hubungannya. Semisal al-Qawiyy, al-Matîn, al-Qahhâr. Sifat Quwat pada Allah ini memiliki unsur keunggulan; kekuatan tiada lawan.
8. Nama yang kembali pada sifat Irâdat beserta tindakan dan berhubungan. Semisal al-Rahman, al-Rahîm, al-Raûf, al-Wadûd. Contohnya, al-Rahman ini kembali pada sifat irâdat-Nya yang behubungan dengan (tindakan) memberikan kebutuhan terhadap kaum lemah.
9. Nama yang kembali pada Zat beserta sifat sandaran. Seperti al-Khâliq, al-Bâri’, al-Wahhâb, al-Mushawwir, al-Mughîs, dan lain-lain.
10. Nama yang kembali pada petunjuk pekerjaan-Nya serta berhubungan. Semisal al-Majîd, al-Karîm, dan al-Lathîf. Nama al-Lathîf menunjukkan pada keluasan keagungan serta kemulyaan Zat-Nya.
Disamping
Asmaul Husna menjadi rujukan (kunci) kesempuraan dan kebahagian
seorang, juga dapat menjamin masuk surga. Bahkan dalam hadits Nabi Saw.
dikatakan: ”Barangsiapa yang berperilaku dengan salah satu akhlak Allah maka ia akan masuk surga”.
Inilah salah satu di antara keistimewaan Asmaul Husna, yang tidak dapat
disamakan dengan nama-nama manusia yang tidak mencerminkan makna sama
sekali. Kalau manusia, namanya Shalih (yang baik) tapi realitas
perilakunya jelek, maka antara nama dan maknanya saling berlawanan.
Yang perlu dicatat, nama-nama Allah Swt. sama sekali bukanlah laqab (julukan, nama lain, alias).
Gambaranya ialah jika ada seorang manusia yang pandai itu disebut
’al-’Alîm’, padahal nama aslinya Badrun, maka penamaan Allah Swt. tidak
seperti itu. Allah Swt. memiliki nama bukan karena unsur sifat-Nya yang
kemudian disematkan (laqab) kepada Zat-Nya, melainkan karena sifat-sifat itu memang menetap tak terpisahkan dari Zat-Nya. Kesimpulannya,
Asmaul Husna menurut Syeh Abi Qasim al-Karkani, termasuk sifat-sifat
Allah Swt. yang tidak akan berubah menjadi sifat manusiawi. Akan tetapi,
mengandung pengertian bahwa Allah Swt bisa memberi hasil yang
dinisbatkan pada sifat-sifat tersebut. Diumpamakan seperti seorang
santri yang mendapatkan ilmu gurunya, akan tetapi gurunya tidak
mendapatkan ilmunya dari si santri.
Nah, melaui Asma’ al-Husna, Allah Swt. dapat memberi manfaat kepada
manusia, tapi Allah Swt. sendiri tidak mengambil manfaat dari apa yang
dilakukan oleh manusia. Wallahu ’Alam []
(Dikutip dari Buku Akidah Kaum Sarungan PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur Indonesia)











 Posted in:
Posted in: 
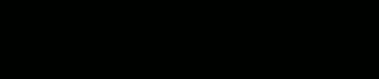
CONTACT